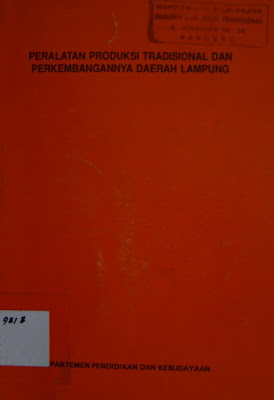Di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat terdapat kesenian yang terancam ditinggalkan. Kesenian khas itu ialah ronggeng gunung. Kesenian ini hanya terdapat di daerah Ciamis dan berkembang di daerah pegunungan. Kepunahan semakin ditakutkan ketika tidak ada penerus yang mau dan mampu menekuni ronggeng gunung.
Sulitnya menekuni ronggeng gunung menjadi salah satu alasan sedikitnya generasi muda yang tertarik. Tidak seperti ronggeng yang lain, ronggeng gunung hanya menampilkan seorang ronggeng. Ronggeng ini pun yang berperan sebagai penari sekaligus juru kawih (penyanyi).
Ronggeng sendiri berasal dari kata renggana yang berarti perempuan pujaan dalam bahasa Sanskerta. Dalam Ensiklopedi Sunda, Alam, Manusia, dan Budaya, sebutan ronggeng hanya diberikan kepada perempuan yang bukan hanya menyanyi, tetapi juga melayani para penonton yang berminat untuk menari dengan imbalan uang.
Seni ronggeng terbagi menjadi tiga jenis jika dilihat dari asal penarinya: Ronggeng Kaler berarti penarinya berasal dari wilayah utara, Ronggeng Kidul penarinya berasal dari wilayah selatan, dan Ronggeng Gunung yang berarti penarinya berasal dari kawasan pegunungan.
Saat ini, hanya ada satu orang yang benar-benar khatam menekuni ronggeng gunung. Ialah yang disebut banyak orang sebagai sang maestro, Bi Raspi. Di usianya yang kini menginjak 65 tahun, ia masih aktif meronggeng di daerahnya untuk acara hajatan dan ritual.
Euis Thresnawaty, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Jawa Barat, mengunjungi Desa Ciulu, Kecamatan Banjarsari, untuk menelusuri Bi Raspi dan kiprahnya sebagai ronggeng gunung. Ia pun membagi perjalanan ronggeng Bi Raspi dalam 4 fase; masa awal karir (1972-1980), masa keemasan (1980-1989), masa vakum (1990-1999), dan masa bangkit (2000-2009). Hasil penelusuran Euis ini pun ditulisnya dalam penelitian yang berjudul “Raspi, Sang Maestro Ronggeng Gunung”.
Euis menceritakan, “Bi Raspi menekuni dunia ronggeng secara tidak sengaja.” Saat itu, Bi Raspi lari dari rumahnya ketika ia masih berumur 13 tahun, baru lulus SD. Pelariannya ini merupakan wujud pemberontakannya karena dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan lelaki bukan pilihannya. Ditambah, saat itu ia masih belum siap menikah muda.
Dalam pelariannya, ia bertemu dengan dua pelatih ronggeng, mbah Maja Kabun dan Indung Darwis. “Bi Raspi menganggap Indung Darwis sebagai gegedug atau ahlinya ronggeng di (Kecamatan) Padaherang,” sebut Euis. Di sini pula ia bertemu dengan teman seangkatannya dalam ronggeng, Bi Pejoh dan Bi Atih dari Pagergunung Pangandaran.
Dalam skripsi berjudul Perjalanan Ronggeng Gunung di Ciamis oleh Yayu Yuniawati, pada tahun 1970-an tersebut keberadaan ronggeng gunung memang sangat dipuja dan dihormati di kalangan masyarakat. Ronggeng gunung diadakan di banyak acara ritual, seperti ruwatan lembur, sedekah bumi, parasan bayi, syukuran sehabis panen, mau menanam padi, dan lain-lain.
Setelah tamat berguru dari Maja Kabun dan Indung Darwis, Raspi pun “dilamar” atau istilahnya ngala ronggeng untuk tampil pertama kalinya sebagai ronggeng gunung. Sebelum tampil untuk pertama kalinya ia dimandikan di mata air keramat yang berada di Kabuyutan Kawasen. Ini merupakan titik awal bagi seorang ronggeng gunung untuk menunjukkan kemampuannya.
Tidak hanya kemampuan lahir seperti menghafal semua lagu ronggeng gunung yang rumit yang diuji. Namun juga kemampuan batin seorang ronggeng gunung yang dianggap sakral. Bagaimanapun, ronggeng gunung tidak hanya berfungsi sebagai penghibur tetapi juga merangkap sebagai sosok yang mampu meruwat. Sosok yang dianggap memiliki kemampuan supranatural.
Sejak itulah Bi Raspi menjadi ronggeng gunung yang eksis sampai sekarang. Hingga saat ini ia sudah menjalani kehidupan sebagai ronggeng gunung selama sekitar 46 tahun. Pada tahun 1970-1980-an ronggeng gunung begitu populer hingga Bi Raspi selalu merasa kewalahan memenuhi panggilan pentas. Ia hanya punya waktu istirahat 3 sampai 7 hari dalam sebulan.
Namun, popularitas itu tidak bertahan lama. Memasuki era 90-an, ronggeng gunung mulai tenggelam di tengah kehidupan modern. Dibanding mengundang kesenian tradisi, banyak orang lebih memilih mengundang pemain organ tunggal untuk bermain di satu acara.
Keadaan ini pun membuat Bi Raspi mencoba melakukan regenerasi ronggeng gunung. Namun, yang terjadi malah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari seni ronggeng gunung menjadi hambatan. “Jangankan mengajar orang lain, anaknya sendiri pun belajarnya kurang serius,” jelas Euis ketika memaparkan keadaan regenerasi ronggeng gunung saat ini.
Neni Nurhayati, putrinya sendiri, memang belum mampu maksimal seperti dirinya yang berperan sebagai penari dan juru tembang. Nani baru berani tampil sebagai ronggeng gunung apabila didampingi oleh ibunya.
Upaya regenerasi ini pun tidak didukung pemerintah sepenuhnya. “Masih ada perlakuan diskriminatif, mengistimewakan kesenian tradisional yang satu dan menganaktirikan kesenian tradisional lainnya,” keluh Euis. Hal seperti ini pun tidak hanya dilakukan pemerintah tetapi juga masyarakat secara individu.
Apa yang terjadi malah ironis. Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran malah saling berebut klaim atas kepemilikan seni ronggeng gunung ini. Bi Raspi sendiri prihatin melihat ini. Menurutnya, pihak pemerintah tidak perlu terjebak oleh asal muasal ronggeng gunung. Seharusnya yang dilakukan adalah kedua belah pihak sepakat untuk melestarikan seni budaya warisan Kerajaan Galuh ini.
Memang, pihak pemerintah sudah memberi ruang agar kesenian tersebut tetap hidup dan berkembang. Misalnya, dengan melibatkannya pada acara sosialisasi suatu program pemerintah atau tampil pada acara syukuran. Namun, langkah tersebut belum terbukti efektif menyentuh akar permasalahan dari terancam punahnya kesenian ronggeng gunung.
Euis beranggapan, “Yang lebih penting lagi, perlu adanya pendokumentasian tentang gending dari tari ronggeng yaitu dengan cara dinotasikan secara lengkap kemudian dibukukan sebelum benar-benar punah.” (ded/ded)